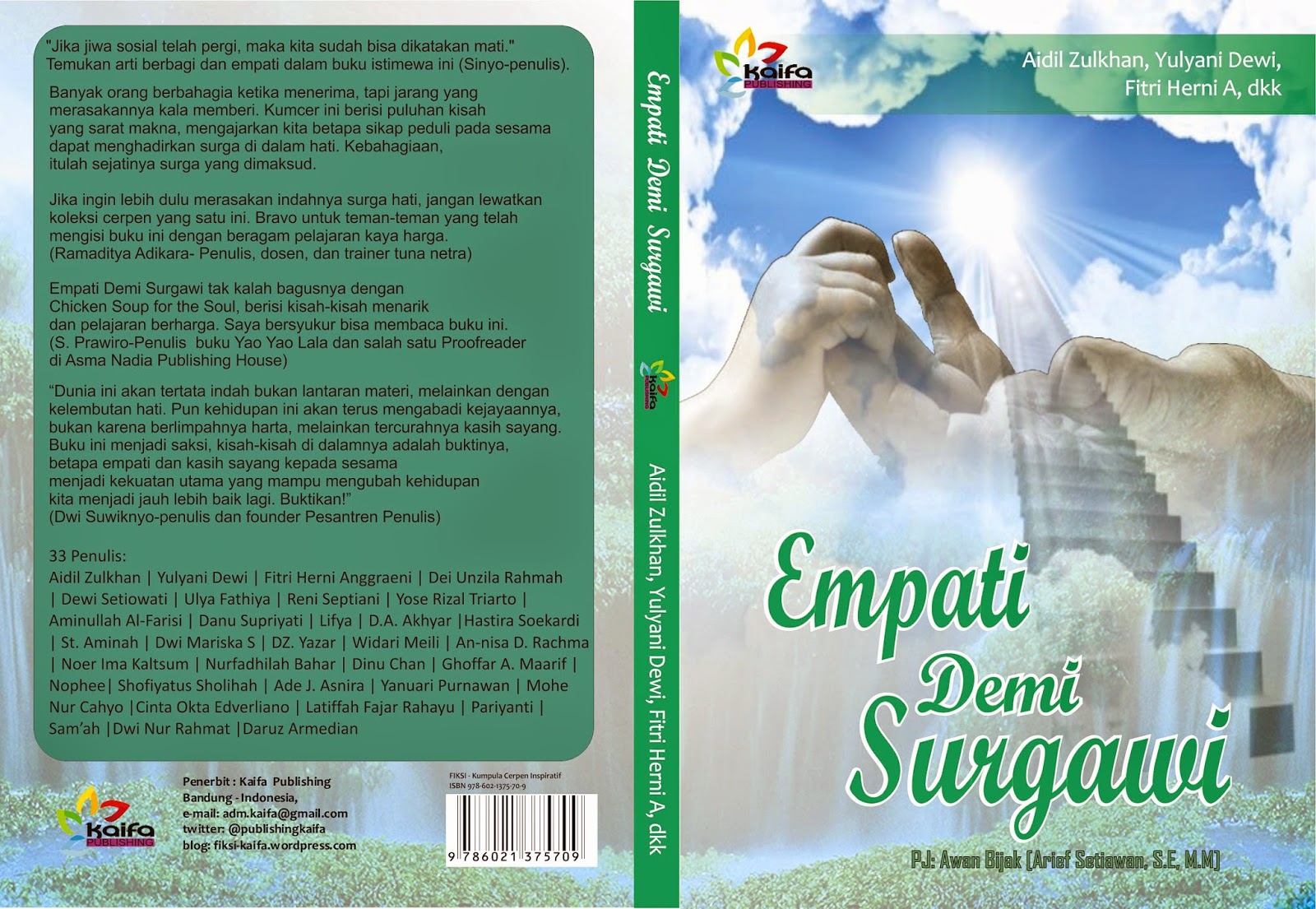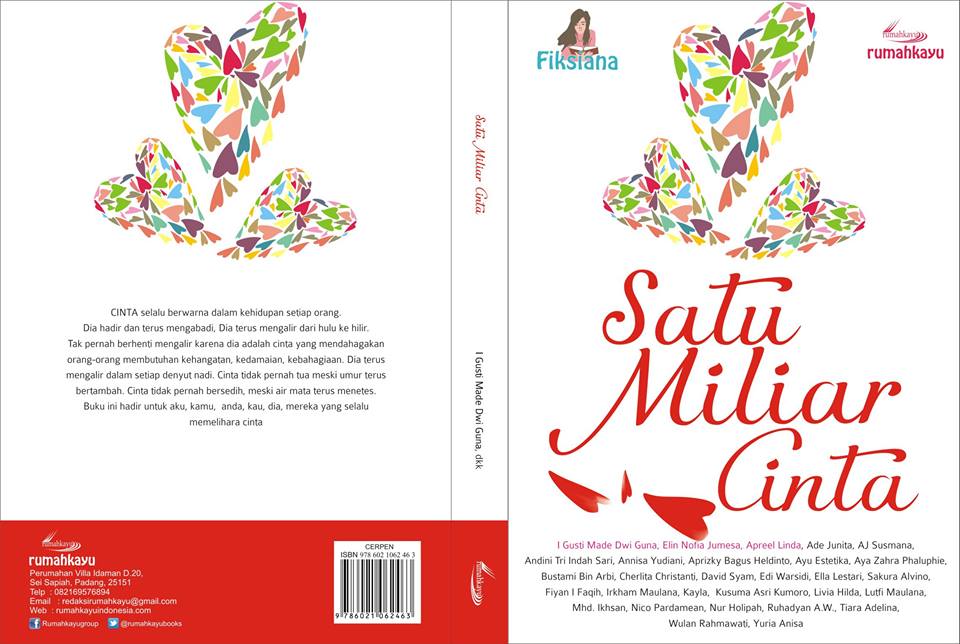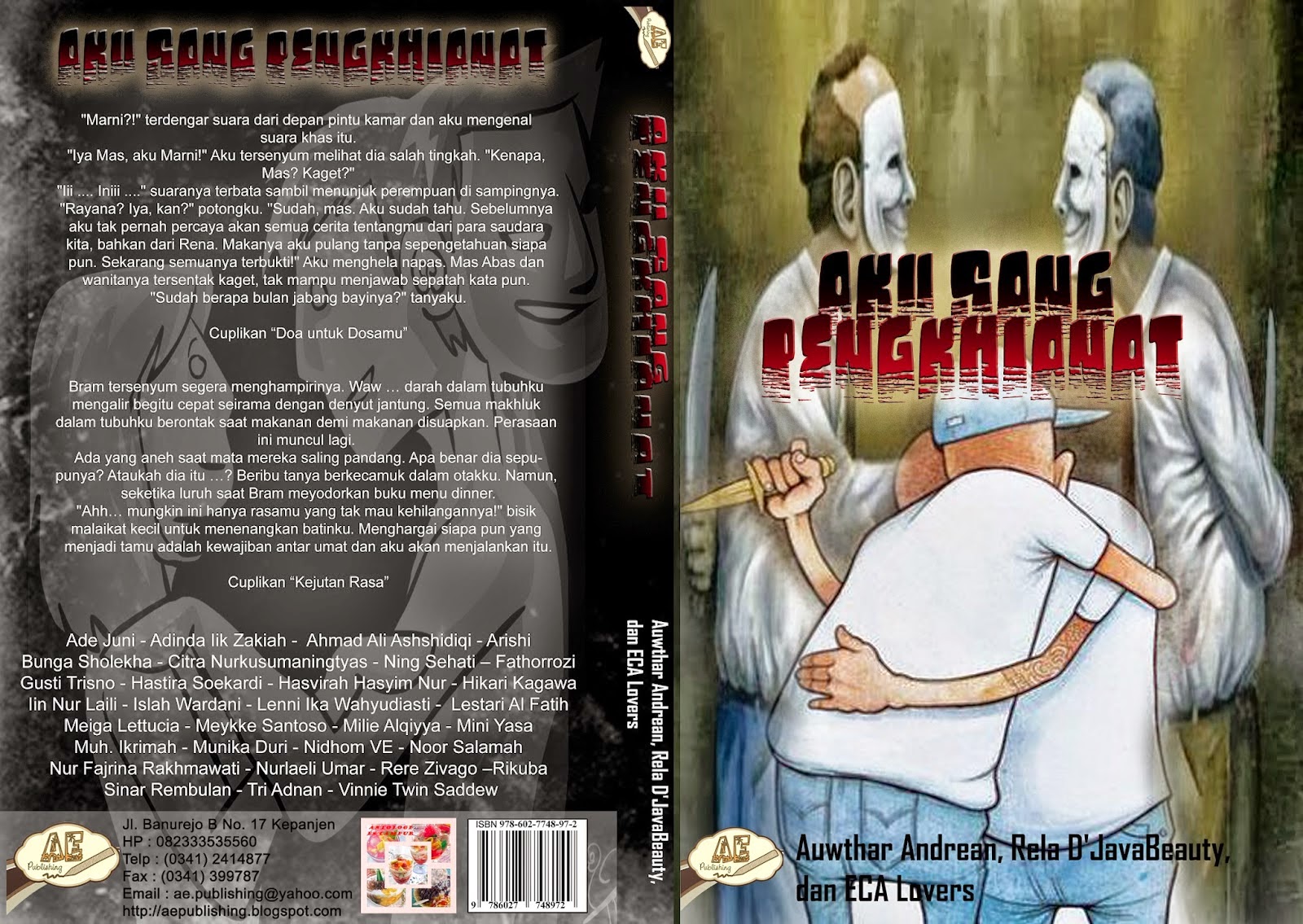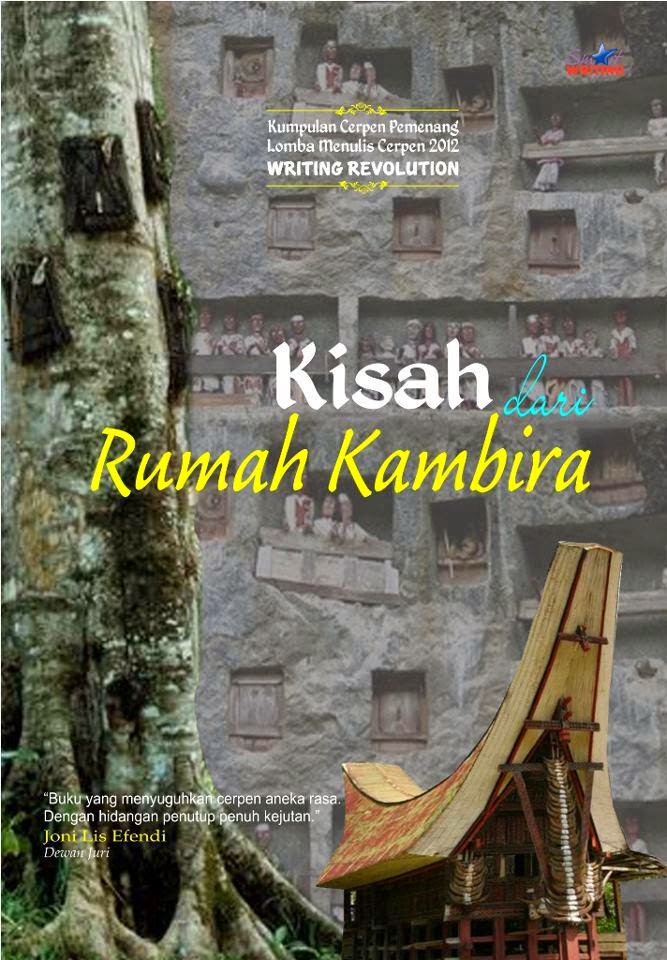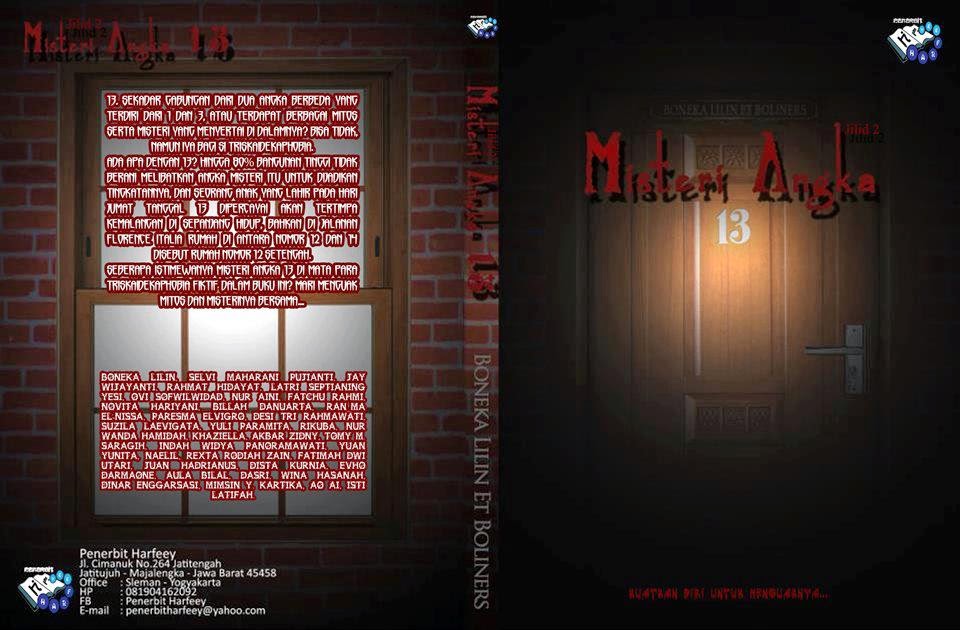Ada
gemuruh yang kembali dan memang masih menyeruak ruang batinnya. Kedatangan
Hilman ba’da dzuhur tadi kembali
menguak rasa pedih yang selama ini tak ingin ia ungkit. Kata maaf tak selamanya
bagai penawar racun yang menyembuhkan sakit dalam waktu singkat. Dirinya tak
pernah mengerti alasan apa yang sampai membuat Hilman meninggalkannya seorang
diri tanpa pesan atau apapun setelah kematian Ibunya.
Air
matanya meluruh cepat melintasi pipi saat mengingat hal itu. Ia benci menjadi
lelaki cengeng seperti saat ini.
Matanya
sendu menatap senja yang meranum di ujung cakrawala. Angin yang menyerbu
menghantam anak-anak rambutnya seakan lari terbirit-birit kabur dari
kesempurnaan senja. Di lantai dua masjid Al-Hidayah ini ia bisa menyaksikan
detik-detik yang menghantarkan senja pada peraduannya dengan fajar di kejauhan
sana.
"Kalau
kau mau, mulailah sekolahmu lagi dan aku yang akan membiayai," kata Hilman
siang tadi. Bukan kasih sayang yang Tiyo rasakan dari kata-kata Hilman, lebih
seperti menganggap Tiyo sebagai sosok yang patut dikasihani.
"Tidak.
Aku betah di Pondok Pesantren ini," tolaknya. Dalam hati ia sudah membuang
jauh-jauh sosok ayah yang ia hargai dan ia hormati. Sempat dilihatnya sorot
mata Hilman yang penuh penyesalan.
Dari
jauh sayup-sayup terdengar kitab bulughul
maram sedang dikaji. Suasana Pondok Pesantren sunyi dengan kesiur daun
pepohonan yang melambai-lambai ditingkahi angin. Di halaman depan sana, Tiyo
meperhatikan sebuah mobil keluaran Jepang yang terparkir. Hingga sedetik
kemudian ia kembali perhatikan sosok di depannya. Benarkah ia ayah yang tega
meninggalkanku? Lelaki yang kini telah memarkir mobilnya di depan sana, lelaki
dengan perawakan tinggi dan berdada bidang juga segaris kumis yang tidak
terlalu lebat melintang di atas bibirnya itu adalah ayahku? tanyanya dalam
hati.
Tapi
tidak, lima belas tahun tanpa kabar, meninggalkannya hidup seorang diri.
Padahal saat itu Tiyo baru berumur 4 tahun. Ia bertahan hidup dengan menjual es
lilin yang ia jajakan di pom bensin. Kemudian membantu menggembala kambing
milik tetangganya, selama itu ia numpang tidur di setiap rumah kerabat yang ia
kenal dan mau mengenalnya. Ia tak kenal sekolah seperti teman-teman seusianya.
Dan Hilman yang seharusnya ada pada saat itu jauh dari jangkauan tangan
papanya. Apakah itu yang dinamakan ayah?
Hingga
ketika berumur sepuluh tahun tetangga yang selama ini Tiyo bantu menggembalakan
kambingnya,
membawanya ke Pondok Pesantren ini. Ia kenal Islam yang mengayomi jiwanya. Jiwa
yang kering-kerontang, tandus tanpa figur seorang ayah yang seharusnya
memberikannya sumber mata air. Maka Pondok Pesantren ini telah menjadi kedua
orang tuanya, bukan hanya sebagai ayahnya.
"Tiyo!
Ayah masih menganggapmu sebagai anakku. Kamu darah dagingku, Tiyo," seru
lelaki di hadapannya memelas.
Tiyo
diam. Ia tidak tahu apa yang mesti ia lakukan tapi ia ingin muntahkan seluruh
penderitaannya saat itu. Tidak! Itu hanya memperburuk keadaan. "Tak ada
yang bilang kau bukan ayahku. Aku juga tetap anakmu. Tapi aku ingin memilih
hidupku sendiri. Hidupku di Pondok Pesantren ini." Ya, kedekatan antara
seorang ayah dan anak yang sering ia lihat pada teman-teman santri sekamarnya
tidak ia rasakan sama sekali pada Hilman. Seakan ada jarak yang kasat mata namun begitu nyata ia rasakan.
"Aku
mengerti keinginanmu, Tiyo. Terima kasih karena kau masih menganggapku meskipun
aku tahu kesalahanku terlalu besar untuk bisa kau maafkan."
Mulutnya
tercekat. Tak tega rasanya melihat pengakuan Hilman. Bagaimanapun juga ia akan
merasa lebih bersalah jika membiarkan Hilman merasa seperti itu. Pun dalam
hatinya, Tiyo mengakui ia sering diserang rasa kesepian karena ketiadaan sosok
ayah. Terlebih setiap akhir tahun ketika sanak saudara dari teman-teman
santrinya berdatangan. Ia rindu dan memang merindui keberadaan ayah. Tapi…,
memang tidak mudah menerima keberadaan seseorang yang datang dengan tiba-tiba.
Adzan
ashar mengakhiri percakapan mereka saat itu.
Barangkali
kenangan memang telah memberatkannya. Barangkali karena kenangan itu juga yang
memakan banyak waktu sehingga untuk menganggap lelaki yang darinya ia terlahir,
sebagai ayah pun bukanlah hal yang mudah. Selama 15 tahun ia hanya mengenal
ayah dari namanya sedangkan wajahnya…, ia tak yakin ia masih mengingatnya
dengan benar. Yang pasti saat lelaki itu mengaku Hilman, ayah kandungnya,
seketika itu juga ia merasa lelaki itu tidak seperti yang ia bayangkan selama
hidupnya. Bukan saja tubuhnya, pun pakaian yang ia kenakan yang kini lebih rapi
daripada dalam ingatannya sewaktu ia masih
kecil.
Dan
mengenai apa yang selama 15 tahun ini Hilman lakukan, Tiyo ingat sewaktu
percakapan tadi bahwa lelaki itu kini telah berhasil menjadi pedagang besar di tanah sebrang, Kalimantan.
Hhh…! Apapun alasannya, tak bisakah lelaki itu memberinya sebuah kabar.
Sempat
ia kesal jika pertanyaan yang kerap kali muncul itu kembali menggangu
pikirannya. Dari kekesalan itu ia sendiri sadar bahwa apa yang sesungguhnya
tarjadi adalah hatinya meretak kembali. Ia ingin membantah semua hal yang
mengatakan kalau orang tua adalah panutan bagi anaknya. Namun sekuat apapun ia berontak, ia tak berani untuk
melanjutkannya.
Tanpa
ia rasa, air mata mengalir dari kedua sudut mata kelamnya. Cepat ia usap air
mata itu. Astaghfirulloh! Kuatkan hati
ini ya Alloh.
***
Senja
memerah di ujung penglihatannya. Sebentar lagi maghrib tiba. Kembali ia tekuni Nadzom Alfiyah di tangannya. Seketika
hatinya terasa ringan, melayang menerbangkan pedihnya. Ia telah mengambil sikap
yang tegas untuk Hilman dan dirinya sendiri, sesaat sebelum kepergian Hilman.
Kendati ia tak pernah bisa menolak dalam jiwanya yang paling dalam ia
merindukan sosok ayah.
“Akhir
tahun nanti aku harap ayah bisa ke sini,” pintanya sebelum Hilman beranjak.
Lelaki
itu tersenyum mendengar permintaan anaknya. “Pasti, Tiyo. Ayah akan ke sini
lagi. Kapanpun itu…”
Tiyo
mengulurkan tangan hendak menyalami dan mencium tangan ayahnya. Namun tanpa ia
sangka, Hilman malah memeluknya begitu erat. Ada haru yang seketika ikut
menyeruak di dalam hatinya. Ia ingin menangis pula. Namun ia hanya bisa
membalas dekapan ayahnya. Setidaknya Hilman juga tahu bahwa selama ini ia
memang merindukan seorang ayah.
Selesai.