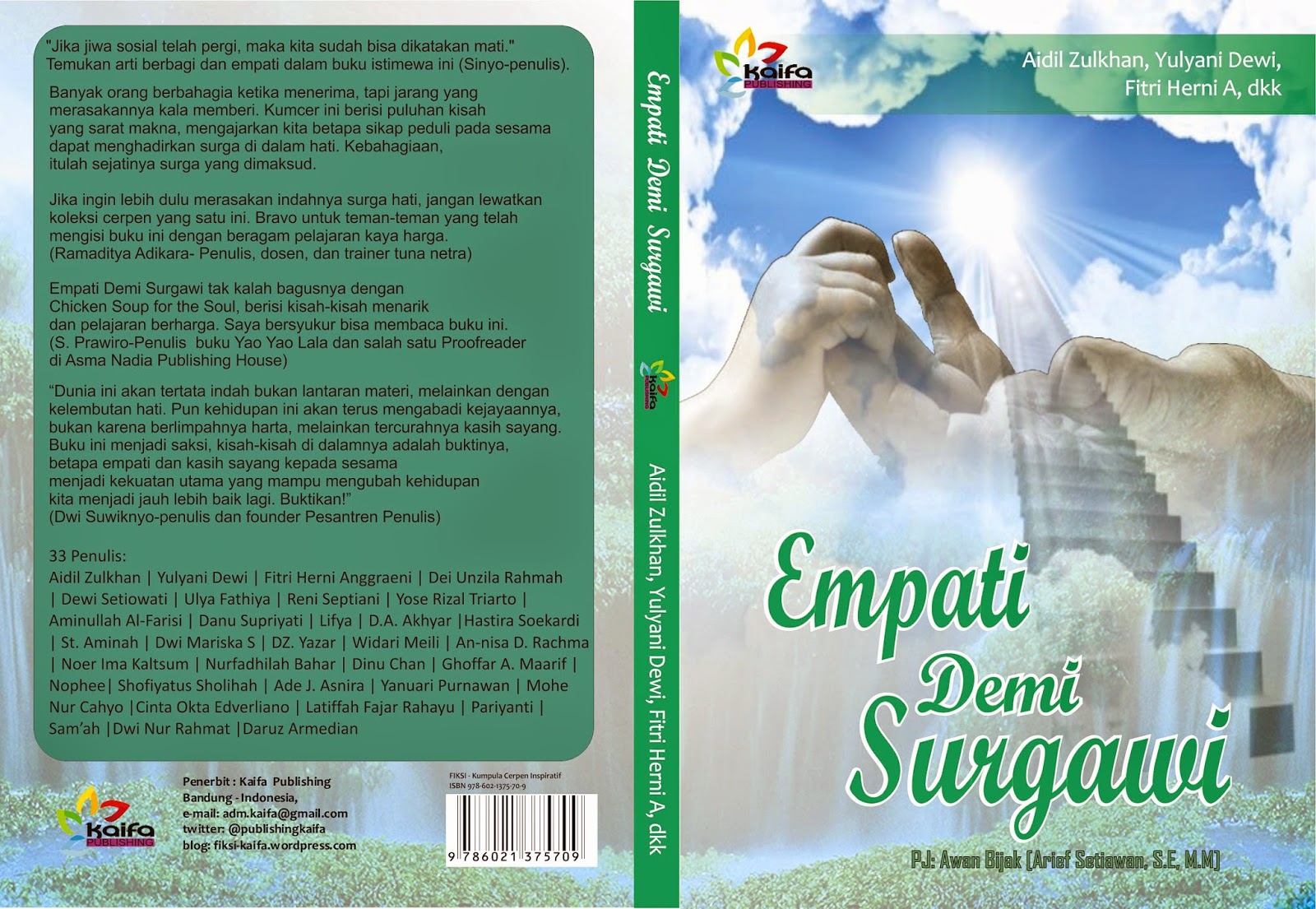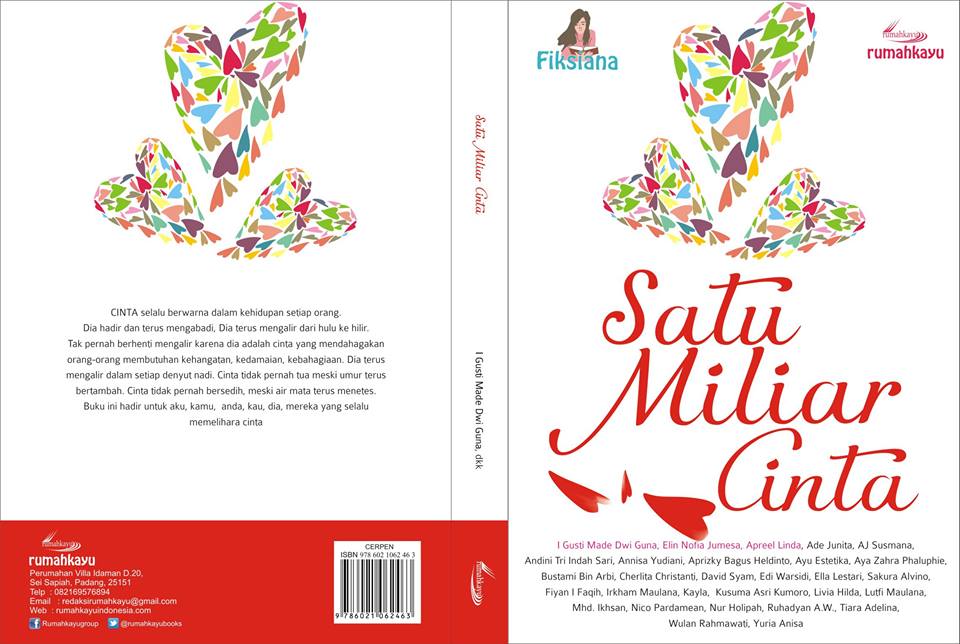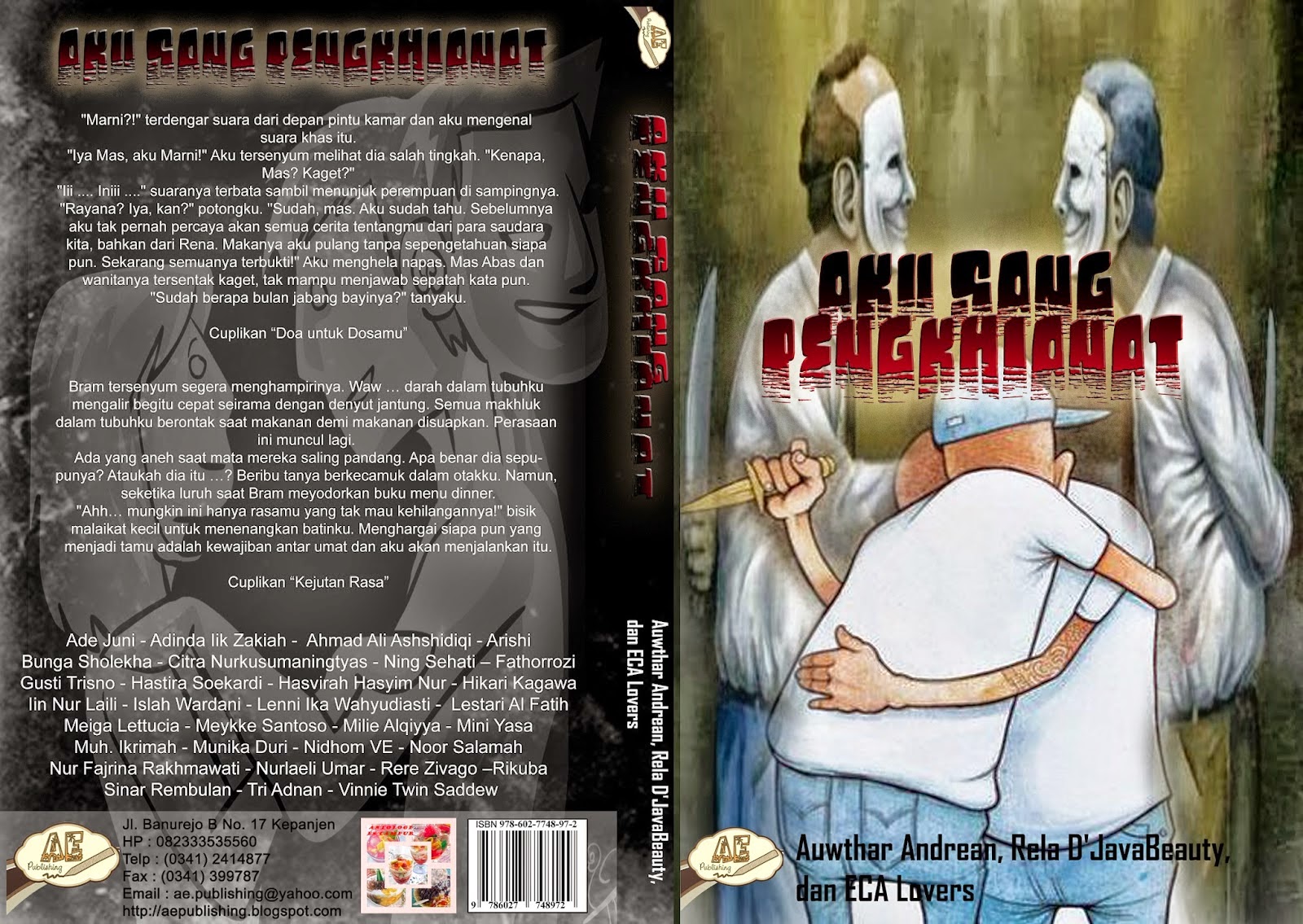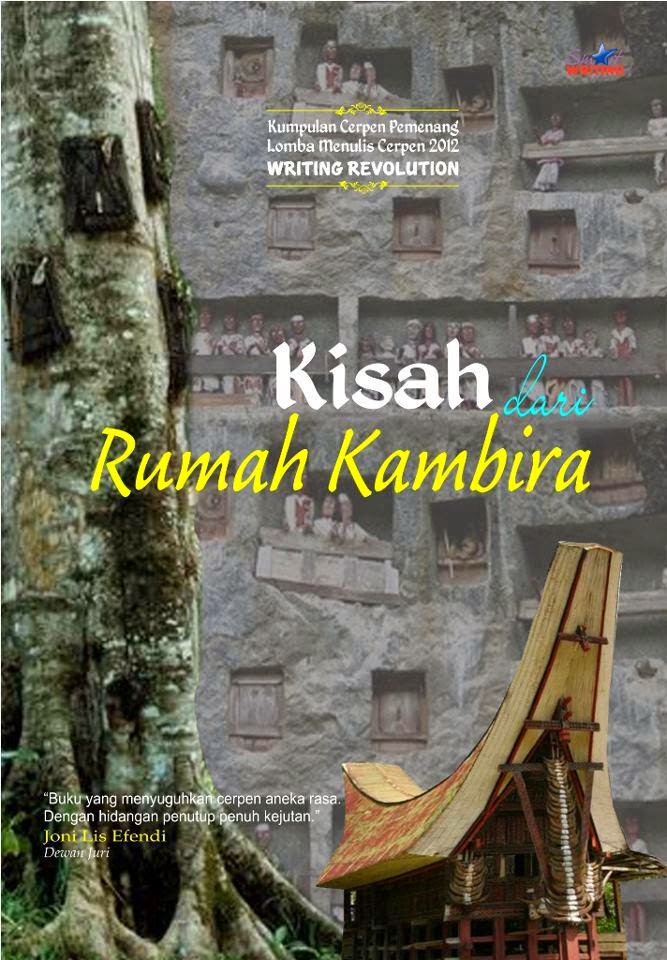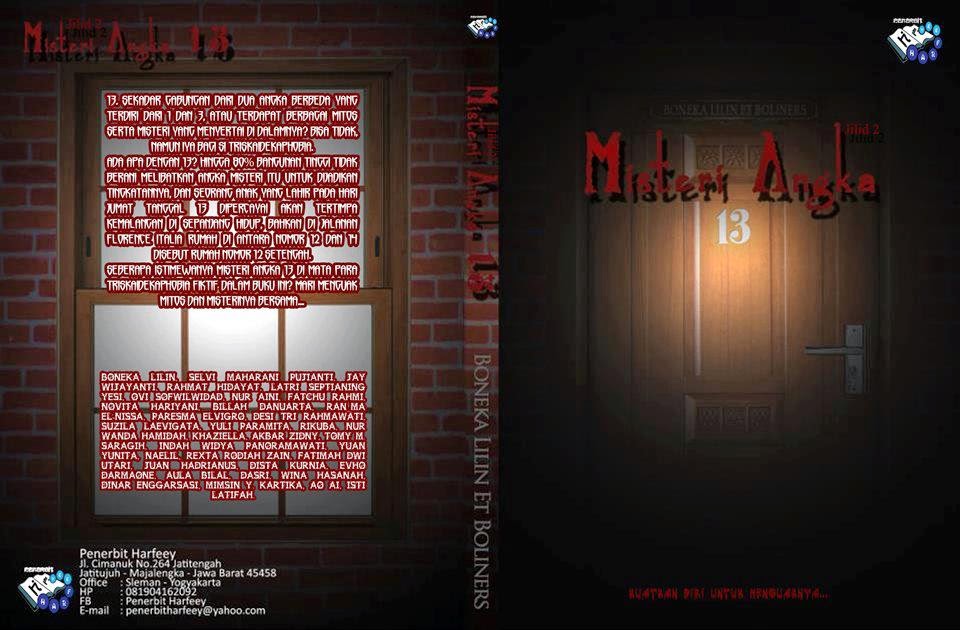Bertambah lagi. Bagi Darjo
detik-detik saat menuliskan jejeran angka itu adalah rasa yang lebih memerihkan, dibanding saat ia harus berusaha
sekuat tenaga untuk menambah penghasilan dengan berbagai cara yang halal.
Betapa hidup ini melelahkan. Selama hidup ia telah berusaha untuk menjadi orang
yang baik dalam artian tidak macam-macam memilih. Bagaimana bisa macam-macam
jika yang bisa ia terima sebenarnya cuma itu saja. Dan ia memang selalu pasrah.
Selalu menerima. Tapi apa nyatanya? Kebutuhan hidup malah terlihat yang lebih
mempermainkannya semenjak anak kedua lahir dari rahim Suciati, istrinya. Dan
tak bisa dipungkiri lagi, saat kebutuhan akan bahan pangan sehari-hari tidak
bisa ditunda barang sehari saja Darjo terpaksa kembali mencari hutang.
Jika diibaratkan, Darjo selalu
merasa bahwa dirinya adalah telur yang sedang berada di ujung tanduk. Dalam
waktu sebentar atau lama dirinya akan menjadi telur yang hancur lebur karena
jatuh dari ujung tanduk itu. Mending kalau ternyata ia masih bisa menjadi telur
di ujung tanduk dalam waktu lama, ia akan mencari-cari cara lebih gigih untuk
tidak lagi menjadi telur. Ia akan berubah menjadi burung atau cicak yang
mempunyai kaki sehingga tidak usahlah khawatir akan jatuh. Tapi kenyataan tidak
semudah imajinasinya. Tidak mungkin ia bisa berada di ujung tanduk dalam waktu
yang lama. Sekarang pun saat hutang yang ia catat sendiri bertambah lagi, ia
merasa waktu saat dimana ia akan jatuh dan hancur berserakan semakin dekat saja.
“Yang sabar, ya Kang. Kita ini
memang tidak punya apa-apa. Hidup sederhana. Penghasilan cuma seberapa. Sebagai
istri saya memang cuma bisa berada di belakang Kang Darjo,” begitu kata
istrinya saat ia membuka obrolan mengenai hutang-hutangnya.
“Iya, Ti. Seharusnya saya yang
meminta kamu bersabar. Saya belum bisa menjadi kepala keluarga yang dapat
menaungi seluruh anggota keluarga dengan kelayakan.”
“Kelayakan bukan dari kecukupan,
Kang. Tapi dari sejauh mana hati kita bisa lapang menerima hidup kita.”
Benar juga. Darjo membenarkan
kata-kata istrinya. Selama ini ia yang sering memberi wejangan-wejangan tentang
hidup kepada istrinya. Tapi baru saja kedua telinganya mendengar kata-kata
bijak itu dari mulut istrinya. Barangkali karena ia terlalu pusing dengan
hutang-hutangnya, pikirannya jadi mampet.
Kini ia bisa menarik dua langkah
yang harus ia lakoni dalam situasi sekarang, menerima dan sabar. Kendati harga
dirinya sebagai seorang suami hampir goyah namun kembali seperti kata-kata
istrinya, kelayakan bukan dari kecukupan tapi dari kelapangan hati menerima
semua. Ahh, betapa bersyukurnya ia bisa mendapatkan istri penyabar sekaligus
pengertian seperti Suciati.
Namun di satu sisi Darjo terus
berjanji untuk bisa mengentas dari kemalangan ini. Meski di satu sisi yang lain
ia tidak berdaya untuk memastikan kalau ia bisa mengentas. Tiba-tiba pikirannya
seakan terbuka dan menanyakan kembali, apakah benar ini kemalangan? Bisa saja
ini adalah uji coba dari Allah untuk membuat ia menjadi lebih pantas menjalani
hidup yang matang bersama keluarga kecilnya nanti. Bukankah selalu ada sisi
baik yang bisa diambil dari setiap kondisi yang buruk. Ya, Darjo tidak akan
menundukkan muka karena malu dengan kondisinya sekarang. Sebaliknya ia akan
berdiri tegak dengan mata menatap lurus ke depan. Ia akan menjadi mujahid yang
memperjuangkan keluarganya dengan sepenuh tenaganya.
***
Belum juga rasa optimisnya melambung
tinggi, kini harus kembali roboh seperti gedung tinggi yang dihantam pesawat
lalu hancur ambruk. Kemarin sore, saat ia masih di tempat kerjaan, mertuanya
datang berkunjung. Suciati yang bertutur padanya. Awalnya memang Suciati tidak
bercerita apa-apa, barangkali jika Darjo tidak menanyakan hal itu pun mungkin
sampai sekarang Darjo tidak tahu menahu. Darjo hanya melihat tatapan aneh dari
tetangganya, juga dari pertanyaan yang dilontarkan tetangganya pada saat ia
pulang.
“Mertuamu tadi ke sini, Jo. Ada apa
ya, Jo? Kok tadi sepertinya ada ribut-ribut…”
Lantas karena pertanyaan itu Darjo
jadi merasa perlu tahu meskipun niat itu tidak segera ia lakukan. Darjo
menunggu waktu yang tepat.
Dan malamnya saat putri kecilnya
sudah tertidur nyenyak, pelan-pelan Darjo mencoba menanyakan hal itu pada
istrinya. Sedikit demi sedikit pula Darjo tahu apa yang sudah terjadi.
Entah
tahu dari mana sehingga di hadapan istri Darjo sendiri alias anak kandungnya,
ibu mertua mencemooh.
“Emang enak hidup sama suamimu
sekarang? Hutang di mana-mana. Suamimu itu, Ti, seperti pengen melumuri wajah
ibumu dengan taik kerbau. Cuiih…!”
Dada Suciati seketika bergidik.
Sebelumnya, walaupun ibunya sering mengungkit-ungkit soal keluarganya tapi
tidak sampai separah ini. Keluarganya memang privasinya yang tidak boleh
diutak-atik oleh orang lain. Dan ketika ibunya mengungkit-ungkit masalah
keluarganya pun Suciati sudah merasa privasinya diinjak. Apalagi sore itu.
“Kualat! Inilah akibatnya karena
kamu tidak menerima lamaran Tejo dulu. Kau lihat sekarang hidupnya, rumahnya
mentereng, punya mobil, sudah jadi PNS bahkan katanya ia pingin buka industry
rumahan yang dikelola istrinya itu.”
“Sudah cukup, Bu! Aku terima kalau
memang ini akibat perbuatanku. Tapi aku tidak terima jika Ibu
membanding-bandingkan Kang Darjo dengan orang lain. Sejelek-jeleknya Kang
Darjo, dia itu suamiku, Bu. Menantu ibu juga,” sanggah Suciati. Ia merasa
privasinya telah diperlakukan seperti barang tak berharga yang tak perlu
dijaga. Ia berontak tetapi bukan ingin melawan perempuan yang telah melahirkannya
melainkan ingin membela diri dan keluarganya.
“Lebih baik Ibu bawa lagi uang ini. Dudu saking kula nolak, Bu, antanapi kula
ngrasa taksih saged nyekapi kebutuhan kula lan keluargi kula piyambek.[1]”
“Hhh…! Dibantu kok ndak mau, sejak kecil kamu memang aneh.”
“Matur
suwun, Bu, sampun mampir teng mriki[2],”
getaran dalam kata-katanya masih kentara terdengar oleh kedua telinga
mertuanya. Lantas Suciati menyalami tangan ibunya saat dilihatnya perempuan
paruh baya itu sudah berdiri hendak pulang.
Perempuan itu hanya diam meski
menanggapi salam dari Suciati. Diam dan dingin. Perempuan yang selalu bisa
berpikiran tenang kendati kakinya sedang berpijak dalam wadah kemelut separah
apapun. Kesan yang sering Darjo lihat pada istrinya pula.
Isak tangis istrinya kini agak
mereda. Darjo bisa ikut merasakan guncangan emosi yang dirasakan Suciati. Dari
bagaimana istrinya menceritakan kembali kejadian itu, Darjo bisa melihat emosi
yang ditahan-tahan istrinya semenjak sore tadi. Pelan tangan kanan Darjo mengelus
pundak istrinya, mencoba menenangkan. Kendati ia tahu istrinya ikut menanggung
beban dari keadaan saat ini namun ia yang lebih bertanggung jawab akan
semuanya. Baik secara langsung ataupun tidak langsung seorang suami adalah
pemegang kendali dari sebuah keluarga. Dan jika diibaratkan, kondisi
keluarganya saat ini adalah sebuah mobil yang mogok dalam perjalanan.
Seketika Darjo berdiri. Tatapannya
sedikit sendu. Suciati nampak ingin bertanya-tanya namun belum terucapkan.
Sampai kaki Darjo mulai melangkah menuju pintu belakang Suciati ikut berdiri.
“Bade
pundi[3],
kang?” tanya Suciati penasaran.
“Mau wudhu, kita minta sama Allah
supaya hati kita tenang. Saya percaya Allah menyelipkan sebuah pelajaran yang
sangat berharga bagi kita dalam masalah ini.”
Suciati mengangguk. Namun tidak ikut
menyusul Darjo. Malah duduk kembali Entahlah.., ia merasa agak malas. Kemudian
beberapa menit Darjo keluar dengan muka basah. Di janggutnya yang pendek
Suciati bisa melihat ada tetes-tetes air yang masih menggelantung di sana.
Didekatinya Suciati yang masih duduk termenung.
“Kok masih di bengong, Ti? Yuk, sholat bareng.”
Agak lama Suciati baru mengangguk.
“Saya tunggu di tempat sholat ya,”
ucap Darjo saat Suciati berdiri.
“Ya,” kata Suciati pelan hampir
tidak terdengar.
Malam itu pun jadi malam hening,
malam perenungan bagi mereka. Untuk mencari cermin yang bisa memantulkan diri
mereka sendiri. Memantulkan diri saat kekurangan demi kekurangan seakan terus
menimpa dan akhirnya memojokkan mereka pada pilihan yang serba salah.
Memantulkan diri saat musibah menindih jiwa mereka lewat tubuh anak kecilnya
yang pekan lalu terbaring lemah karena dilanda demam yang sangat tinggi,
sehingga Darjo dan Suciati harus membawanya ke rumah sakit. Juga cermin yang
bisa memantulkan diri mereka saat kehadiran anak keduanya semakin memosisikan
diri mereka pada tempat dimana semakin terasa terpuruk dan bukan sebaliknya. Seperti
inikah hidup? Tiada henti menimpa dan menempa.
Palimanan,
12
April
2015
15:05:59
*Dimuat di majalah Indosuara edisi Maret 2016 Th.X Vol.05/113