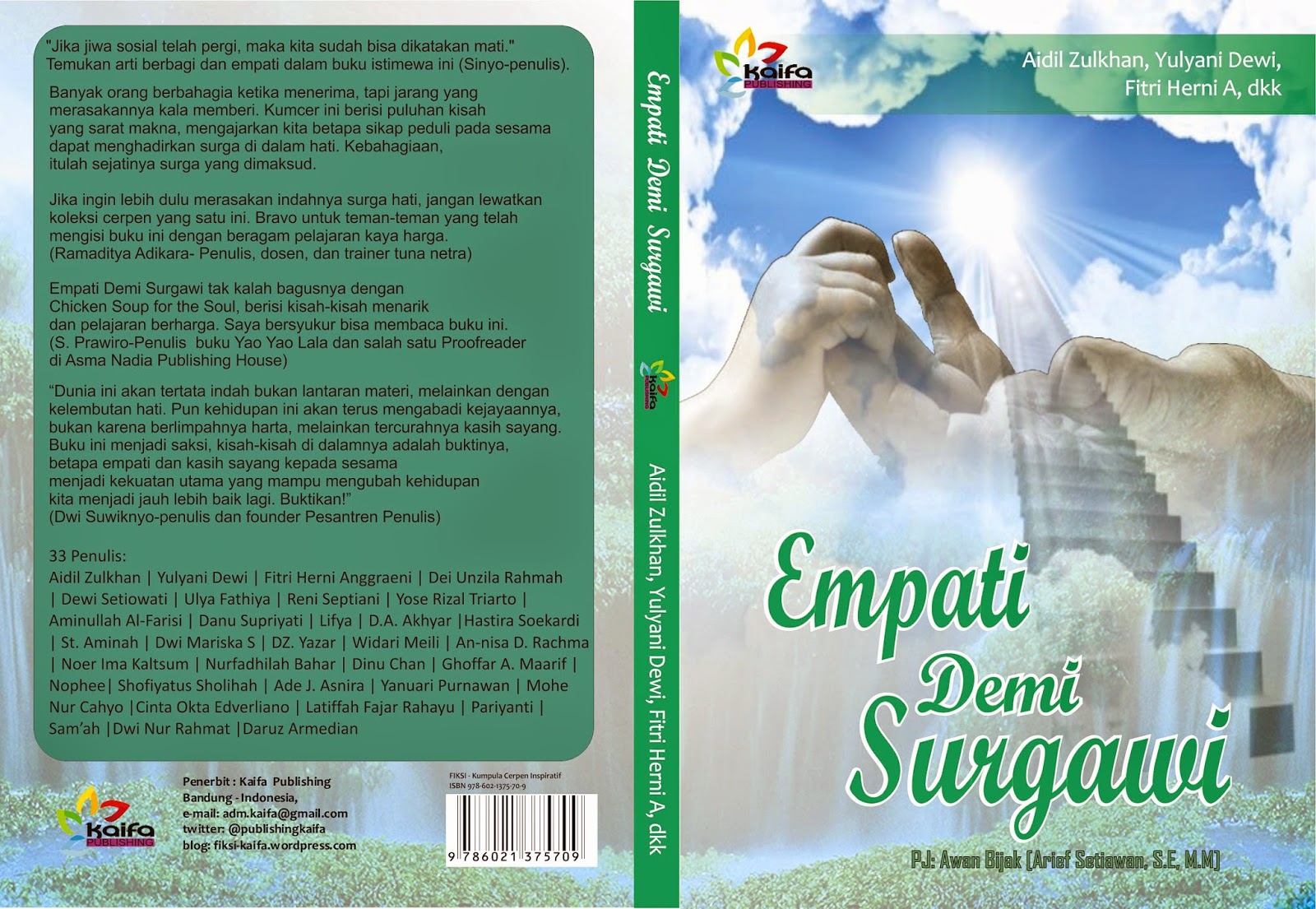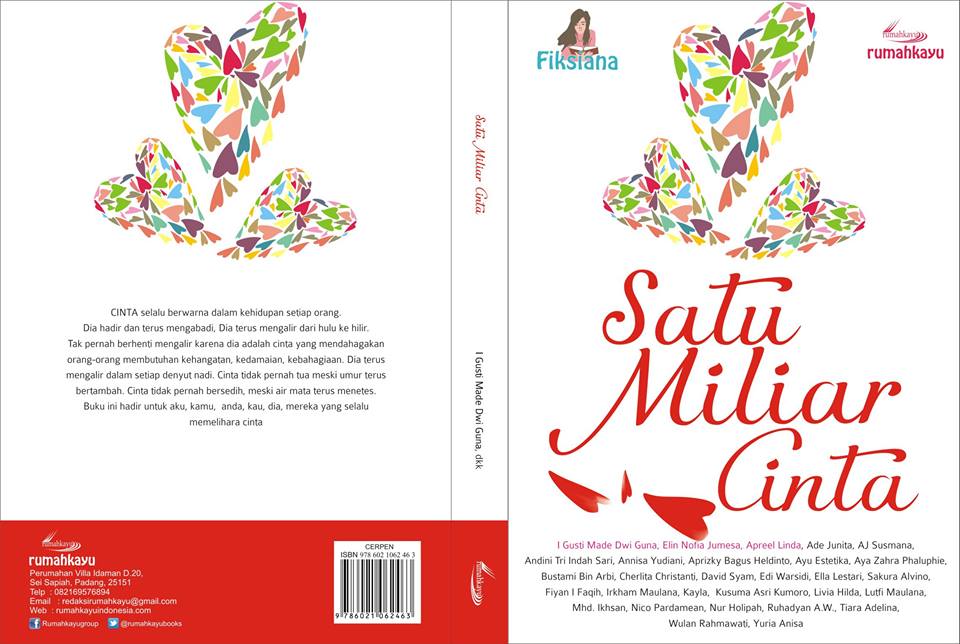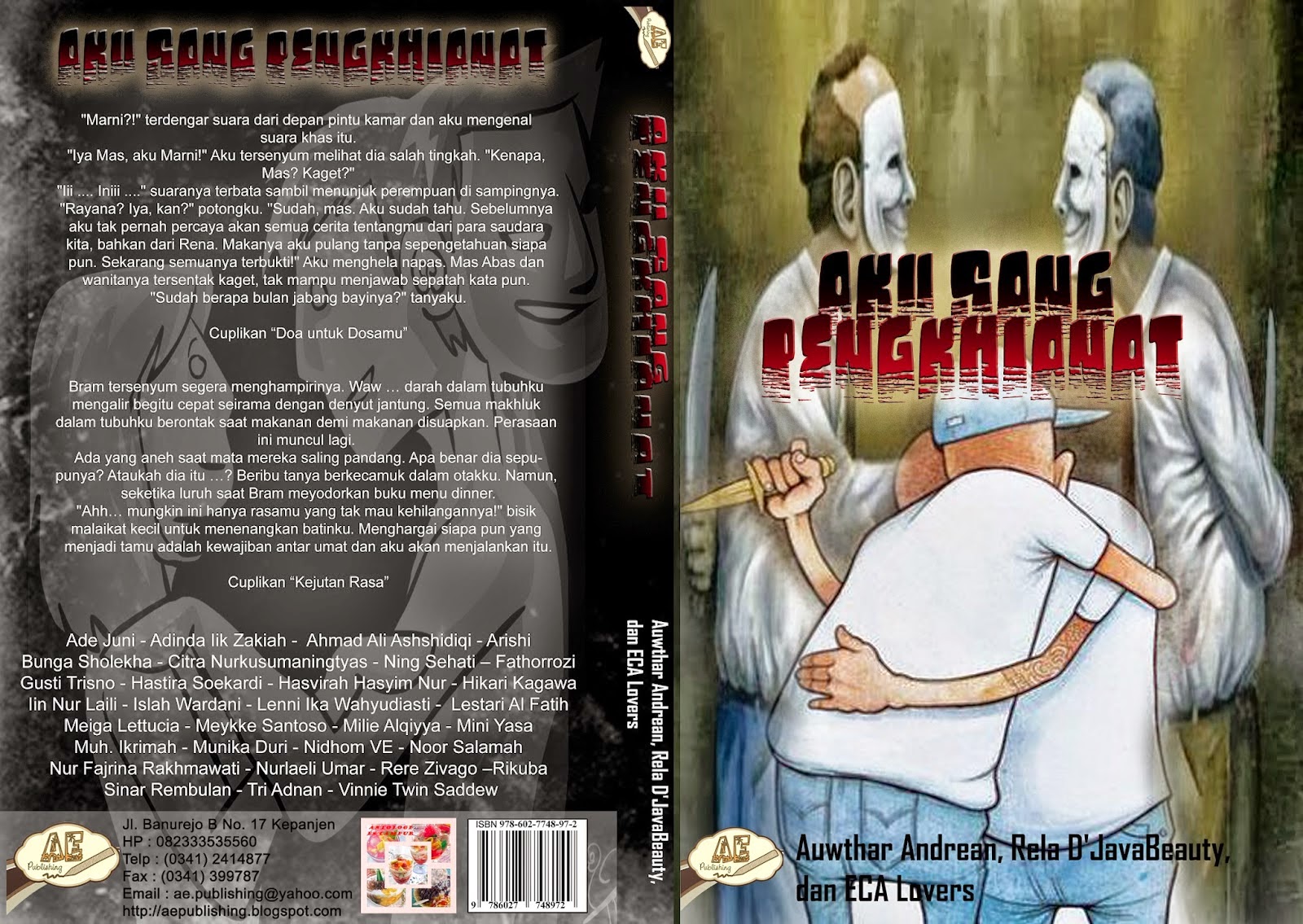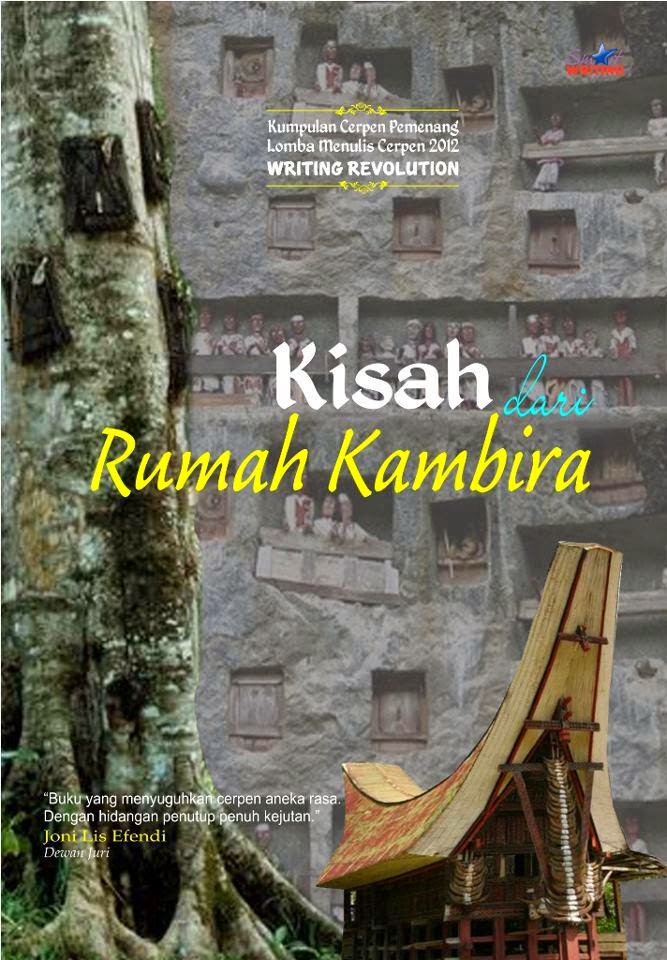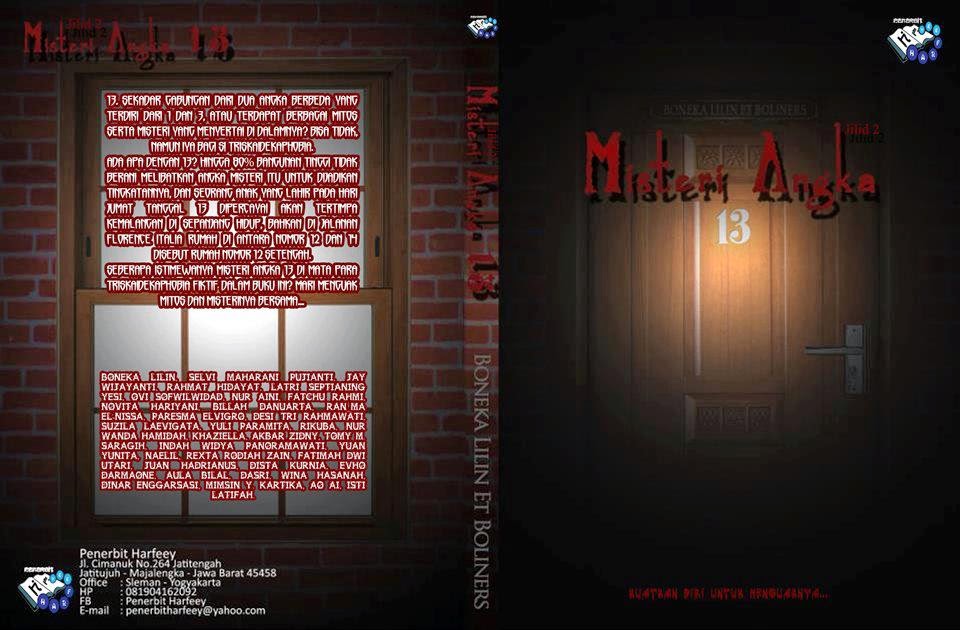Ala Bisa Karena Biasa (Hanya untuk yang suka menulis)
Peribahasa/ungkapan tersebut
lebih menyatakan bahwa segala sesuatu bertahap entah untuk hal yang sepele
seperti belajar mengendarai sepeda ataupun untuk hal yang besar seperti daya
kreatifitas yang dimiliki oleh kita semua. Meskipun tahapan-tahapannya kecil
namun (kembali pada peribahasa di atas) jika dilakukan secara berkesinambungan
maka akan menuai hasil yang memuaskan, lincah saat bersepeda sampai-sampai pada
saatnya menjadi atlet internasional misalnya atau membuat sebuah inovasi yang
menakjubkan di mata dunia karena daya kreatifitas yang begitu tinggi. Itu semua
bisa saja terjadi.
Namun sayangnya kita
cenderung menyorot pada hasil dari apa yang telah dicapai oleh seseorang. Dan bukan
pada seberapa lama ia berusaha sampai titik berhasil itu atau pada seberapa
keras ia berusaha untuk bisa mencapai titik tersebut.
Seperti halnya seorang
penulis sekelas dengan Mba Helvy Tiana Rosa atau adiknya Mba Asma Nadia atau
juga Pak Seno Gumira Ajidarma. Entah seberapa lama dan sekeras apa mereka
menekuni dunia menulis tahu-tahu kita mengenal mereka sebagai penulis sastra
papan atas negeri ini. Sebenarnya ini hal lumrah karena kita adalah penonton
bagi orang lain. Dan tentunya tidak salah juga kita menjadi penonton bagi diri
kita sendiri atau meminjam ungkapan lain yakni instropeksi (dalam hal menulis
tentunya).
Mari kita coba menengok
kembali kesalahan-kesalahan kecil kita pada tulisan kita sendiri. Bisa jadi
kita baru menyadari kesalahan-kesalahan kecil itu sekarang. Mari kita lebih
teliti untuk menilik kembali anak kreatifitas kita dalam bentuk tulisan yang
sering kali kita bangga-banggakan sampai begitu PEDEnya kita kirimkan tulisan
itu pada media atau pada lomba-lomba dengan skala luas.
Mulai dari seperti apa
susunan kalimat kita, seperti apa kita memilih kata -secara kata dalam bahasa
Indonesia sangat kaya-, lalu seperti apa cerita yang kita ambil dan dituangkan
dalam tulisan. Dan coba kita bandingkan dengan karya Mba Helvy Tiana Rosa, Mba
Asma Nadia atau Pak Seno Gumira Ajidarma. Pasti ada beda dan tentu karya kita
tidak bisa disamakan dengan karya mereka, wong mereka penulis kolot kok. Paling
tidak kita bisa mengambil contoh dari karya mereka. Dan paling tidak kita tahu
bahwa dengan daya kreatifitas kita, kita bisa mencuri tips-tips dari karya mereka.
Perhatikan tiap pemilihan katanya, pengungkapannya, penegasannya, alurnya,
plotnya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah bisa memperhatikan secara detail
tiap kalimat dari karya mereka saatnya kita memperhatikan secara detail pula
karya kita. Lihatlah apa yang terjadi pada diri kita.
Hasil dari semua itu
memang tidak bisa langsung kita terima dan sadari. Bukan hasil yang menjadi hal
utama namun proses yang perlu kita utamakan. Karena ‘proses’ menempa kita, ‘proses’
mengasah kita, ‘proses’ pun mengajari kita.
Ala bisa karena biasa. Ketika
kita membiasakan diri untuk lebih teliti pada karya diri kita maupun karya
orang lain maka sejatinya kita sedang membawa perbaikan pada daya kreatifitas
kita sendiri.
Salam Semangat Menulis !
sumber gambar : http://elektrikbank.blogspot.com/2013/04/pentingnya-menumbuhkan-minat-menulis.html